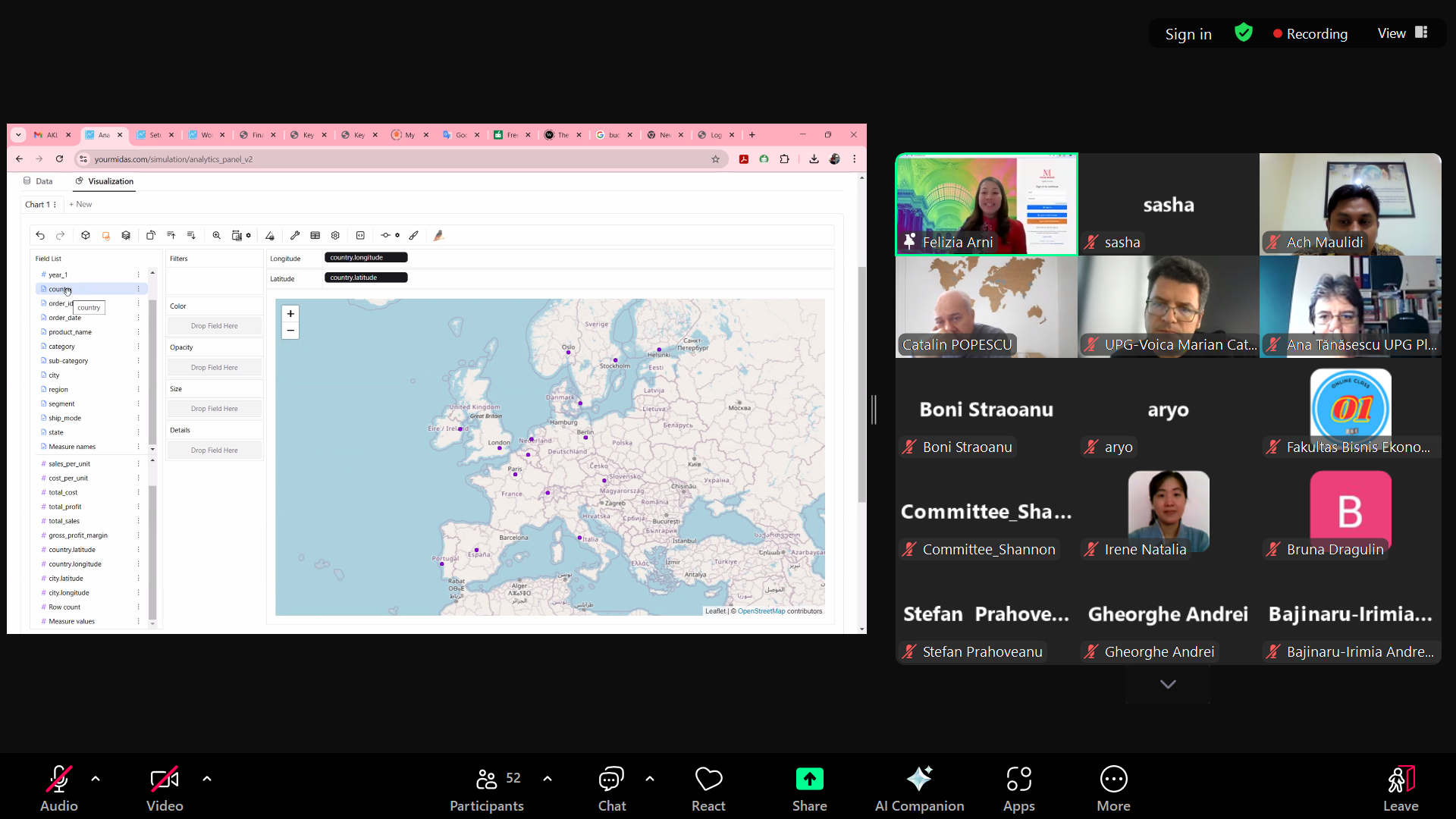Meski Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga ad hoc, ternyata perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak masih terlalu lemah. Terutama perlindungan bagi mereka yang menyandang status korban perceraian. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan jaminan hak biaya hidup dan biaya pendidikan seperti yang seharusnya.
Untuk mengulas lebih dalam tentang dampak perceraian dari kacamata psikologi, wartawan Suara Karya di Surabaya, Andira, mewawancarai psikolog dari Universitas Surabaya (Ubaya) Dra NK Endah Triwijati, MA.
Dosen Fakultas
Psikologi Ubaya itu juga merupakan pendiri Savy Amira, sebuah pusat penanganan krisis bagi perempuan korban kekerasan, terutama keshy;kerasan dalam rumah tangga. Berikut petikannya.
Belakangan makin sering saja muncul kasus perceraian yang tidak menguntungkan pihak istri dan anak-anak yang bersangkutan, hingga akhirnya muncul wacana pembentukan UU khusus untuk melindungi mereka. Bagaimana menurut Anda?
Sebelumnya saya ingin meluruskan tentang dampak dari sebuah kasus perceraian. Selama ini kebanyakan orang menganggap perceraian selalu berkonotasi negatif terhadap anak-anak dan istri yang bersangkutan. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Justru saya melihat, banyak keluarga yang menjadi lebih baik saat sepasang suami-istri yang bermasalah itu memutuskan untuk bercerai.
Mengapa bisa demikian?
Dari sisi psikologi, para istri dari keluarga bermasalah itu sebetulnya tertekan karena setiap hari harus terlibat dalam pertengkaran dengan suaminya. Tapi kebanyakan, karena berbagai alasan, mereka memilih tetap bertahan menerima kekerasan dalam rumah tangga.
Para istri dan pihak keluarga istri hingga kebanyakan masyarakat telanjur bepersepsi bahwa keluarga itu akan hancur apabila akhirnya harus terjadi perceraian.
Padahal yang terjadi tidak demikian. Bahkan kalau pertengkaran rumah tangga disertai kekerasan dibiarkan, justru dampaknya akan negatif. Anak-anak mereka akan makin terbiasa melihat ibunya ditempeleng, dicaci maki, dan setiap hari dipaksa melihat pemandangan tentang ibunya yang murung dan menangis.
Bagaimana dampaknya bagi anak-anak ke depan?
Dalam situasi seperti itu, anak-anak yang setiap hari melihat ibunya tertekan cenderung berharap kedua orang tuanya itu bisa segera berpisah. Tapi, kebanyakan mereka hanya bisa pasrah dan tidak bisa memaksa ibunya untuk rela dicerai. Apalagi perceraian sama sekali tidak dikehendaki oleh ajaran agama mana pun.
Pihak keluarga kebanyakan juga akan meminta mereka bertahan karena menganggap perceraian itu ibarat kiamatnya sebuah keluarga. Keluarga sang istri juga khawatir anak-anak mereka akan dicap sebagai produk keluarga gagal, yang pada gilirannya akan menghambat proses untuk mendapatkan jodoh kelak.
Dalam kasus perceraian, sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab atas biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka?
Selama ini, masalah besar yang melatarbelakangi kasus perceraian adalah faktor ekonomi. Sesuai ketentuan, seharusnya ayah biologis mereka tetap harus bertanggung jawab secara finansial untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak mereka hingga berusia di atas 18 tahun. Tapi faktanya, mayoritas mantan suami itu tidak peduli lagi dengan mantan istri dan anak-anak biologis mereka.
Memang ada juga ayah yang masih peduli dan mau membiayai anak-anak mereka. Tapi, jumlahnya sangat sedikit. Kami bahkan sering menemukan kasus ada seorang istri dengan dua anak yang terpaksa bercerai karena tidak tahan dengan pukulan suami. Usai dicerai, dia bekerja seadanya, tapi belum saja cukup untuk memenuhi kebutuhannya dengan dua anak. Suatu saat, ketika dia tidak punya uang karena tidak di-support mantan suaminya, kedua anaknya yang kelaparan itu diminta untuk minum air sebanyak-banyaknya dan diminta tidur, agar bisa mimpi makan yang enak-enak.
Menurut Anda, siapa yang salah dalam kasus seperti ini? Atau memang benar UU khusus melindungi korban perceraian tidak diperlukan?
Jujur saya akui, posisi istri dalam keluarga memang serba salah. Aparat penegak hukum (APH) juga kerap berlaku tidak adil. Mereka dituntut lebih peka lagi terhadap masalah gender. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering kami tangani, para istri korban kekerasan itu justru kerap menjadi tersangka.
Misalnya, tentang seorang istri yang dianiaya suaminya secara bertubi-tubi. Secara logika, wajar kalau sang istri itu bereaksi spontan melakukan perlawanan, misalnya dengan mencakar wajah sang suami.
Ironisnya, justru APH lebih berpihak kepada sang suami. Hanya karena si suami lebih dulu melaporkan kepada polisi dengan membawa bukti visum tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan. Kalau APH dibiarkan tetap saja begini, saya yakin, kaum perempuan korban kekerasan rumah tangga akan lebih memilih mendiamkan kasusnya itu karena khawatir mereka yang nanti akan dijadikan tersangka.
Sumber: https://www.suarakarya.id