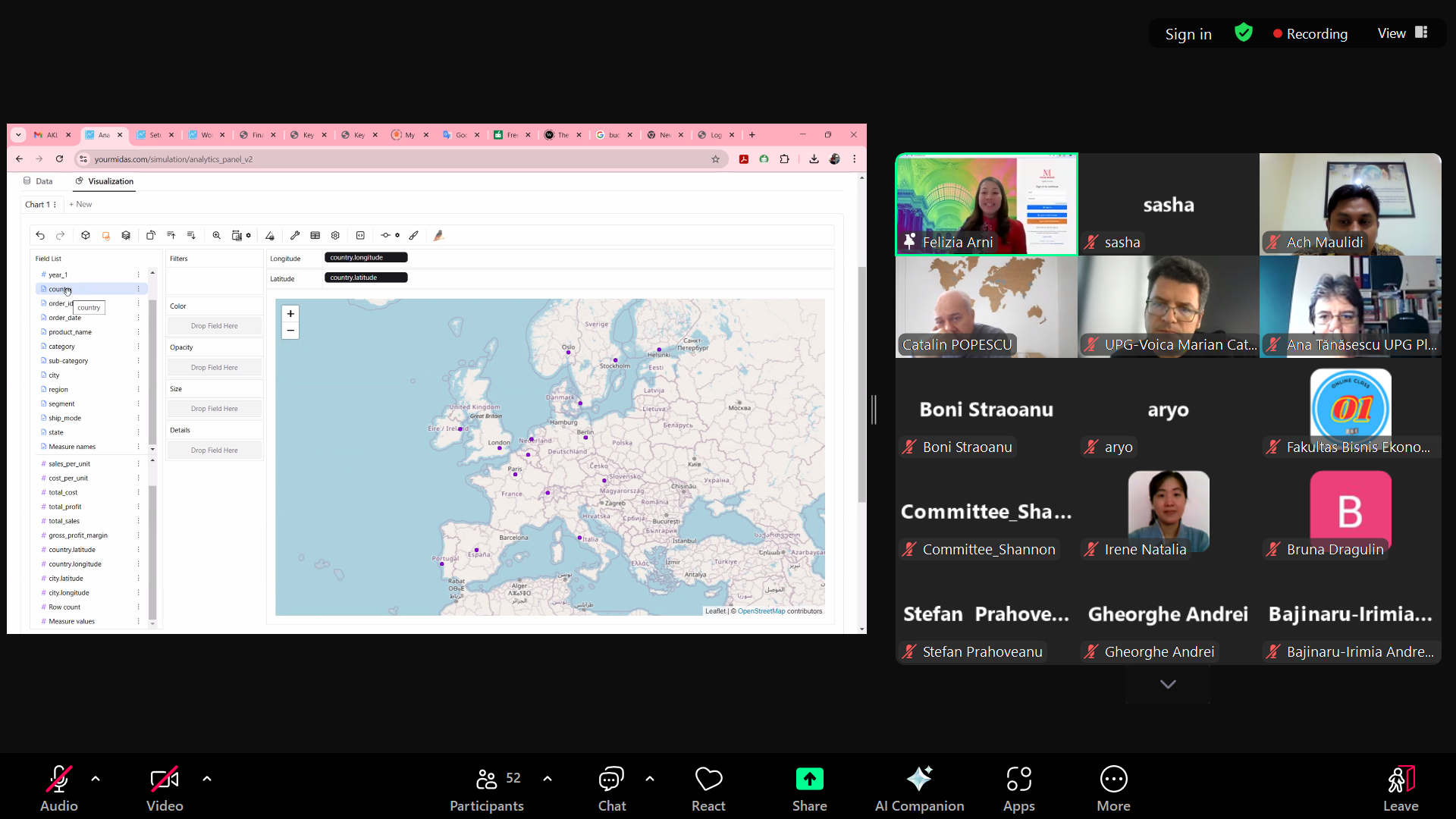Mahasiswi Jepang Rela Tinggal di Kos-kosan Sepur.
Selama sepuluh hari, 6-15 Agustus 2008, lima anak muda dari Indonesia dan Jepang menggelar Indonesia International Work Camp (IIWC). Mengangkat isu Difabel Community, mereka menikmati tinggal di rumah keluarga penderita cacat.
PERAYAAN sederhana digelar di Joglo Pusat Pemberdayaan Masyarakat Kota (Pusdakota) Ubaya, Minggu malam lalu. Tak lebih dari sepuluh orang hadir. Ada yang ngobrol, memegang gitar, dan mengutak-atik keyboard. Di ujung kiri terdapat beragam makanan. Ada tumpeng, sushi, tempe goreng, roti dan sebagainya.
Dengan iringan keyboard, sebuah lagu meluncur dari bibir Yuria Okuno dan Akina Takuma, dua peserta dari Jepang.
Konna koto iina dekitara iina,
anna koto iina.
Konna yume konna,
ippai arugedo
Teks tersebut memang terasa asing. Tapi nadanya sangat akrab di telinga. Sebab, itu lirik asli lagu dalam film kartun Doraemon. Karena itu, peserta lain dan undangan yang hadir bisa menirukan akhir lagu tersebut,
Totemo daisuki, Doraemon.
Kami memang sengaja me-request lagu itu. Sebab, lagu Jepang yang paling dikenal warga sini ya itu, kata Bahrul Fuad, koordinator Center on Difabel Community Development and Empowerment (Confident) Pusdakota.
Yuria dan Akina adalah peserta biasa disebut volunteer Indonesia International Work Camp (IICW) of PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Jawa Tengah. Bersama tiga volunteer lain dari Indonesia, mereka merayakan penutupan home stay di rumah keluarga penyandang cacat.
Para volunteer tersebut menjalani home stay selama dua hari satu malam, Sabtu dan Minggu lalu. Sebagai ‘perpisahan’, hadir juga tiga keluarga tuan rumah home stay dalam perayaan tersebut. Selanjutnya, mereka tinggal di sebuah rumah di Gubeng Kertajaya.
Kegiatan itu, kata Widy Dinarti, kepala Camp IICW, merupakan agenda tahunan IICW. (Agung Putu Iskandar)
Tak Canggung Tidur di Ruang Tamu
Isu yang diambil kali ini adalah difabel community atau masyarakat penderita tunagrahita. Tahun lalu isunya anak-anak jalanan, jelas mahasiswa semester tujuh Hubungan Internasional Unifersitas Airlangga itu.
Home Stay dilakukan di rumah-rumah warga yang punya anggota keluarga tunadaksa (cacat fisik) di kawasan Rungkut. ‘Agar mereka merasakan bagaimana kehidupan orang-orang difabel dalam lingkungan keluarga,’ ungkapnya.
Yuria Okuno dan volunteer dari Indonesia, Fapyane Deby, kebagian tinggal di rumah Hasan di Rungkut Lor. Hasan dan istrinya penyandang tunadaksa. Ketika dikunjungi Sabtu lau, Yuria sedang sibuk di dapur. ‘Saya belajar bikin soya bean milk,’ ujar wanita 21 tahun itu dalam bahasa Inggris logat Jepang.
Hasan tinggal di kawasan padat penduduk. Dua sepeda onthel khusus penyandang cacat diparkir di depan rumah berukuran sekitar 5 x 4 meter itu. Berdinding tembok dengan dua kamar tidur. Satu kamar ditempati Hasan dan Istrinya, kamar yang lain untuk putri, menantu, serta cucu-cucunya. Sedangkan Yuria dan deby tidur di ruang tamu.
Meski begitu, dia enjoy saja. ‘Ke kamar mandi pun dia tak pernah mengeluh,’ kata Deby. ‘Sekali dia bertanya, mengapa persediaan air di kamar mandi tak pernah melimpah,’ lanjut mahasiswi Farmasi Unair tersebut.
Siang itu cukup panas. Yuria mengenakan kaus oblong abu-abu bergambar anak kucing tidur di sebuah jaring. Di bawahnya terdapat tulisan don’t disturb.
Tanpa canggung, tangannya mengaduk seonggok ampas sisa pembuatan susu kedelai dalam piring. Mencampur dengan tepung dan telur, kemudian digoreng. Hasilnya, mirip nugget. ‘Ini namanya soya bean nugget,’ jelas Deby. Untuk memakan nugget itu, harus menggunakan saus tomat.
Tinggal di rumah keluarga difabel memberi pengalaman berharga bagi Yuria. Terutama sikap terhadap penyandang cacat. ‘Di sini yang bukan penyandang cacat dan para difabel berbaur. Tidak ada yang diistimewakan. Semua bergaul seperti orang normal,’ katanya.
Di lingkungan kampung Hasan, yang normal maupun yang cacat tidak ada perbedaan. Misalnya, berbincang, kerja bakti, dan melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga. ‘Mereka juga bercanda dengan cara yang sama seperti kepada orang normal,’ ungkap Yuria.
Mahasiswi semester empat Hubungan Internasional Doshisha University tersebut mengaku tak pernah menemukan hal seperti itu di Jepang. Di negaranya, penyandang cacat selalu diberi fasilitas untuk mempermudah mereka dalam aktifitas sehari-hari. ‘Tapi, fasilitas-fasilitas itu seperti memisahkan mereka dari pergaulan dengan masyarakat nonpenderita,’ tegasnya.
Di Jepang, tutur Yuria, penderita cacat tidak tinggal bersama orang normal. Mereka harus tinggal di sebuah bangunan khusus yang dilengkapi fasiitas untuk orang cacat.
Hal yang sama terjadi di kampus dan apartemen. Penderita cacat hanya bisa masuk universitas yang punya fasiitas untuk mereka. ‘Saya memang tidak pernah tahu bagaimana perasaan para penderita itu,’ katanya. ‘Tapi, dengan adanya pembedaan-pembedaan itu, warga nonpenyandang cacat seperti enggan berbincang dengan penyandang cacat. Mereka melihat penyandang cacat seperti orang yang khusus,’ lanjut dia.
Pengalaman serupa dirasakan Akina Takuma yang tinggal di rumah keluarga Sukamto bersama rekannya, Resi Alfina, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Undip, Semarang. Sama seperti Hasan, Sukamto penyandang Tunadaksa. Dia tinggal di kos-kosan sepur. Rumah kos yang kamarnya berderet-deret seperti gerbong kereta.
Kulit Akina yang putih tampak bintul-bintul. Sesekali, dia menggaruk. ‘Gatal karena nyamuk,’ ujarnya lirih dalam bahasa Indonesia.
Akina adalah mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Kyoto Sangyo. ‘Guru saya mengatakan, masuk jurusan bahasa Indonesia mudah. Sebab, alfabetnya sama seperti pronounciation,’ jelasnya.
Namun, mahasiswi semester empat itu belum lancar berbahasa Indonesia. Dia selalu berpikir dulu sebelum berkata dalam bahasa Indonesia.
‘Ada perbedaan antara masyarakat Jepang dengan Indonesia,’ katanya lantas terdiam.
Setelah mencoret-coret sesuatu di block note-nya, dia melanjutkan kata-katanya. ‘Masyarakat sini sangat terbuka. Mereka sudah biasa menerima orang asing atau orang yang lain dari mereka,’ sambungnya.
Dalam penutupan itu, Akina mendapat kado dari Pusdakota. Dia tampak terkejut. ‘Di Jepang, saya tidak pernah menerima hadiah dari orang asing,’ katanya. ‘Orang yang baru kenal pun tidak bisa memberi hadiah. Di sini, semua terasa begitu mudah,’ ungkapnya dengan alis mengernyit.(efu)
Sumber: Jawapos, 12 Agustus 2008